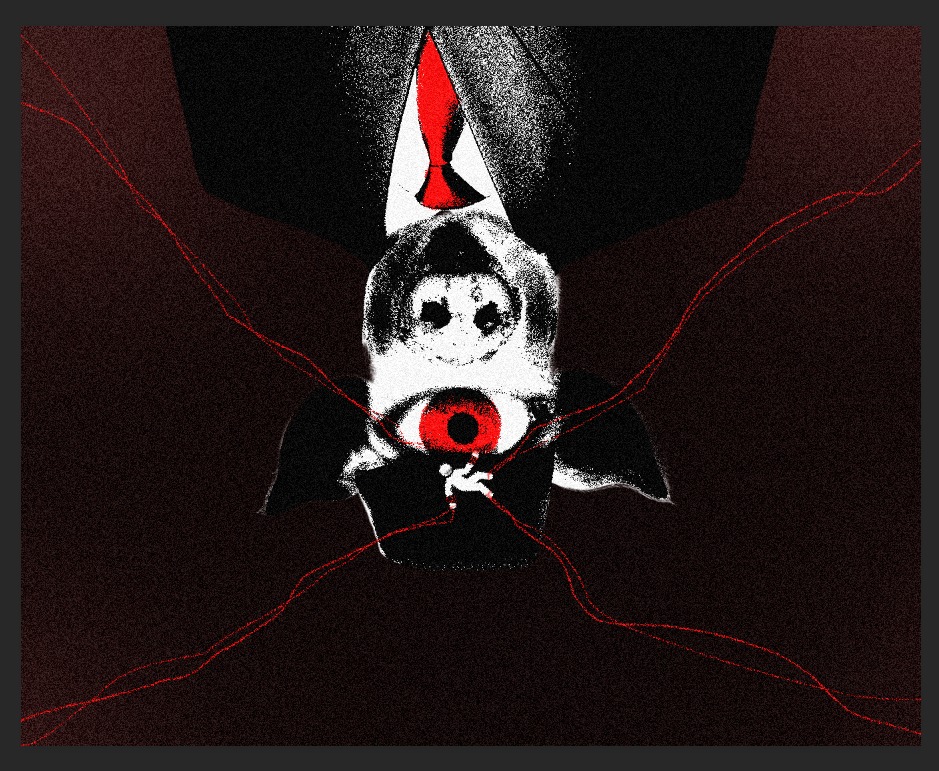
©Rizqi/Bal
Pasca-Reformasi, kita masuk dalam era Neo Institutional Economics (NIE), yang ditandai dengan menguatnya institusi-institusi negara dalam mengatur kegiatan perekonomian untuk mengurangi biaya transaksi tinggi dalam pembangunan ekonomi. Era ini mensyaratkan instrumentalisasi hukum sebagai sarana untuk mendukung kegiatan ekonomi. Pembuatan kebijakan atau Undang-Undang (UU) akan diarahkan untuk memaksimalkan aktivitas pasar. Salah satu produk hukum NIE pada masa pasca-Reformasi adalah UU Pemerintah Daerah. Desentralisasi merupakan ciri khas dari NIE melalui penyederhanaan proses birokrasi tersentralistik yang mahal dan rumit menjadi efisien dan sederhana.
Dengan konsep ini, pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui UU Pemerintah Daerah memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan proses administratif pengelolaan sumber daya lokal dengan melibatkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerah. Cara ini diharapkan dapat membuat jalur birokrasi dan pengelolaan ekonomi daerah dapat disesuaikan dengan kekhasan lokal, termasuk di antaranya perihal perizinan, kebutuhan terhadap aturan-aturan pelaksanaan kegiatan bisnis, perdagangan, dan investasi.
Selain desentralisasi, produk NIE mewujud dalam penegakan hukum dan antikorupsi. Proses pelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UU KPK yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan DPR menjadi jalan bernas untuk memberantas korupsi dan kolusi yang menjadikan aktivitas ekonomi berbiaya mahal. Dengan penegakan hukum, negara hadir untuk menjadi penjamin bahwa aktivitas bisnis, perdagangan, dan investasi terbebas dari para penggarong. Dua produk hukum dalam masa lahirnya NIE di Indonesia melahirkan harapan terhadap penyelenggaraan negara yang akuntabel, transparan, efisien, dan partisipatif.
Harapan tersebut sejalan dengan tesis pembangunan inklusif milik Amartya Sen dkk (2011). Ia menyarankan bahwa pengelolaan negara harus didasarkan pada beberapa aspek krusial seperti kebebasan berpolitik, fasilitas ekonomi, kesempatan sosial, jaminan transparansi, dan keamanan protektif. Desentralisasi memperkuat peran masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pengawasan politik di daerah. Pelembagaan KPK memperkuat proses pengawasan terhadap penyaluran sumber daya dalam bentuk fasilitas ekonomi dari pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum, bukan untuk kepentingan elite atau golongan tertentu. Dengan demikian ada garansi dalam pengelolaan sumber daya negara yang transparan sehingga layanan-layanan sosial dan ekonomi dapat menjangkau masyarakat.
Selang waktu berlalu, harapan-harapan bernas itu pun diusik. Jika kita menggunakan pendekatan teori agensi dari Michael C. Jensen dan William H. Meckling (1976), oligarki politik membuat agency theory ‘biaya agensi’ dari rakyat tidak bernilai. Kita ibaratkan DPR dan presiden itu sebagai agen dan rakyat sebagai prinsipal. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi mendelegasikan aspirasi dan pengambilan keputusan kepada para agen. Jadi, agen diberi wewenang mengatur negara, tetapi sesungguhnya harus tetap menguntungkan rakyat.
Jika kita tetap berpedoman pada teori keagenan, kita bisa menelusuri bahwa revisi UU KPK justru berpeluang melemahkan ruang gerak komisi anti-rasuah tersebut. Ilustrasinya seperti ini, kita anggap KPK merupakan satu-satunya komisi yang dipercaya oleh the real principal ‘prinsipal yang nyata’. Tugasnya untuk mengawasi kinerja agen karena seringkali agen memiliki kepentingan yang bertolak belakang dengan prinsipal. Agen yang ruang geraknya dibatasi tidak bisa melakukan lobi-lobi bisnis dan politik yang mendatangkan keuntungan bagi the fake principal ‘prinsipal yang palsu’. Akhirnya, ruang gerak KPK dibatasi.
KPK dijadikan sebagai bagian dari lembaga eksekutif agar dapat dikontrol. Upaya penyidikan mereka dibatasi agar agen korup bisa leluasa melanggengkan tugas mereka bagi prinsipal yang palsu maupun mengembalikan political costs ‘biaya politik’ agen yang korup itu. Pembentukan dewan pengawas semakin mempersempit ruang gerak KPK, apalagi jika dewan pengawas dipilih oleh presiden atau DPR. Penyadapan juga harus seizin dewan pengawas agar tidak leluasa menelusuri jejak korupsi.
Setelah Reformasi, para oligarki mulai menunjukkan taji juga mempengaruhi proses penyusunan RUU Cipta Lapangan Kerja (CiLaKa). Sekalipun banyak aksi demonstrasi menolak rancangan tersebut, pada akhirnya RUU disahkan juga pada 2 November 2020 lalu. UU CiLaKa merupakan langkah memutar balik yang dilakukan pemerintah dan DPR dari ruh NIE menjadi Law & Neoliberal Market dan Law & Developmental State. Poin intinya adalah karena UU CiLaKa menyerahkan sepenuhnya proses birokrasi investasi menjadi satu pintu melalui Online Single Submission yang dikelola pemerintah pusat. Tentu, hal ini bertujuan untuk menyederhanakan aturan-aturan yang tumpang tindih antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam upaya penarikan investasi. Penyederhanaan ini tidak hanya berbicara tentang efisiensi, melainkan juga menjadi langkah pasti untuk mengurangi partisipasi masyarakat lokal secara politis dan ekonomi.
Pemerintah pusat menjadi agen penjamin bagi pelaku bisnis dan investor dalam proses penyelenggaraan aktivitas ekonomi berbiaya murah dengan penyederhanaan birokrasi secara sentralistik. Langkah ini akan mengesampingkan dampak-dampak turunan seperti hilangnya partisipasi publik, potensi konflik dengan masyarakat adat, hingga tak terjaminnya hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan perekonomian daerahnya. Kita bisa melihat lingkungan dirusak, hak-hak masyarakat adat direnggut, dan sumber daya dikelola oleh korporasi. Janji pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja yang tinggi di kemudian hari hanya menjadi mimpi. Jika pun itu menjadi realita, ia hanya dinikmati oleh elite oligarki dan golongan tertentu saja.
Saya sengaja melakukan dua eksperimentasi ide dengan membandingkan kinerja lembaga tinggi negara di masa lalu yang cukup ciamik dengan kinerja mereka hari ini yang mengesampingkan aspirasi. Pada akhirnya, kemarahan publik yang memuncak pada lembaga tinggi negara yang tak menjalankan fungsi semestinya pun menjadi hal wajar. Tak heran jika kemudian rakyat menuntut pembubaran. Rakyat sudah jengah, rakyat sudah lelah. Namun, tuntutan ini pun perlu kita telisik bersama, benarkah pembubaran lembaga tinggi negara ini menjadi urgensi?
Indonesia adalah penganut sistem trias politica. Sistem ini mensyaratkan pembagian kekuasaan negara menjadi tiga lembaga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini dibuat sebagai upaya untuk mencegah kekuasaan absolut yang sewenang-wenang. Negara membutuhkan kontrol antarlembaga tinggi negara guna memastikan penyalahgunaan kekuasaan tidak terjadi. Kita mungkin melihat sistem ini tak berjalan semestinya akhir-akhir ini karena satu dan lain hal, tetapi bukan berarti gagal sebagai sistem.
Sistem ini membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat dari para aktor politis di dalamnya, syukur-syukur jika diisi dengan proses meritokrasi. Sayangnya, aktor-aktor politis ini tak menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik sehingga membuat sistem ini terlihat mengalami malfungsi internal. Namun, apakah pembubaran salah satu lembaga negara menjadi jalan satu-satunya? Tentu tidak. Mengapa?
Kita musti menilik kembali sejarah bangsa ini. Kita perlu mengingat saat negeri ini masih mencari jati diri, praktik demokrasi mengalami pasang surut. Kala itu, kita bisa melihat Soekarno-Hatta saling “adu jotos” dalam narasi. Dwitunggal Soekarno-Hatta luruh menjadi dwitanggal ketika Soekarno terlena dalam tampuk kekuasaannya. Perpecahan politik keduanya mulai terlihat kala Hatta mengesahkan Maklumat X pada November 1945 untuk meletakkan sistem multipartai dan demokrasi parlementer.
Namun, ketika perkelahian antarpartai mulai tampak menjengkelkan, Soekarno mengambil langkah memutar balik dengan menyerang Hatta dan berusaha menggugurkan Maklumat X yang diteken Hatta. Puncaknya, pada tahun 1956, Soekarno merencanakan demokrasi terpimpin dan bertekad “mengubur” semua partai. Perseteruan tak berhenti di situ, Hatta menyerang balik dengan menyebut upaya Soekarno sebagai upaya mencapai visi kediktatoran. Akhirnya dengan kepala tegak dan dengan kesadaran penuh untuk menjaga harkat dan martabat moralitas politiknya, Hatta mengundurkan diri dari posisinya sebagai wakil presiden pada 20 Juli 1956.
Pada akhirnya, sejarah mencatat bahwa ketakutan Hatta terjadi. Distopia visi kediktatoran Soekarno menjadi momok bagi bumi pertiwi. Sekalipun Soekarno menyatakan bahwa ia bukanlah seorang diktator, tetapi keputusan-keputusan politisnya mengarah pada kediktatoran. Ia membungkam oposisi lewat pembatasan kebebasan berekspresi dan pengelolaan perekonomian tanpa pengawasan yang menyebabkan hiperinflasi. Ini tentu tak lepas dari peristiwa yang sebelumnya terjadi. Melalui Dekrit, Soekarno “menggugurkan” ide Hatta tentang pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang awalnya merupakan Badan Pembantu Presiden menjadi lembaga legislatif setara presiden (eksekutif) dan menjadi cikal bakal lahirnya DPR.
Jika kita membaca novel 1984 yang ditulis oleh George Orwell (2016), narasi kediktatoran merupakan distopia yang amat menakutkan. Dalam novel tersebut, Orwell menarasikan dengan sangat jelas betapa kehidupan dalam sistem totalitarianisme absolut adalah kehidupan yang tidak bisa dinikmati sama sekali. Totalitarianisme adalah bentuk pemerintahan yang memiliki kendali mutlak dan terpusat atas seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik publik maupun pribadi, melalui propaganda, penindasan, dan paksaan. Ciri khasnya adalah adanya satu partai politik tunggal, seorang pemimpin tunggal yang kuat, dan penolakan terhadap kebebasan individu demi kepentingan negara atau ideologi kolektif.
“BIG BROTHER IS WATCHING YOU”, begitulah Orwell menulisnya dalam novel. Yang disebut sebagai “Big Brother” bukanlah figur, melainkan sistem yang mengawasi sebagai kekuasaan absolut. Ia dapat mengubah fakta sejarah, menciptakan bahasa baru sesuai kepentingan (newspeak), dan melakukan propaganda pikiran (doublethink). Segala tingkah laku masyarakat diawasi dengan ketat melalui telescreen. Ada pula polisi pikiran yang bertugas memastikan masyarakat tak mengkreasi ideologi selain ideologi negara. Jika ada yang berusaha memberontak, maka nasibnya akan “dihilangkan” dari sejarah. Totalitarianisme ini tak menghendaki kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia sehingga partisipasi politik aktif dari masyarakat dalam penyelenggaraan negara.
Apa yang dinarasikan oleh Orwell dalam novelnya sedikit banyak memberi gambaran bahwa “absolute power tends to corrupt”. Dengan ini, maka pembubaran DPR tak memiliki urgensi. Jika ia memang butuh koreksi, ya, hal tersebut dapat dilakukan. Koreksi ini bisa terus kita lakukan melalui pengawasan dari masyarakat sipil yang menjadi pilar dalam penyelenggaraan demokrasi. Namun, kita punya pekerjaan rumah yang besar yaitu bahwa kita perlu meneguhkan kembali visi kolektif masyarakat sipil yang tampak hampir roboh. Berbagai narasi diusung untuk mematikan ruang gerak mereka.
Pertama, partai politik (parpol), sekalipun parpol bukan merupakan bagian langsung dari masyarakat sipil, tetapi parpol memiliki peran krusial sebagai alat kontrol demokrasi. Parpol yang seharusnya membawa kepentingan masyarakat sipil justru dibajak oleh kaum oligarki yang menguasai tubuh internal parpol.Bentuk utama dari oligarki politik di parpol adalah hadirnya orang-orang kuat sebagai para penentu keputusan yang direpresentasikan oleh orang-orang bermodal kapital dan sosial amat besar. Jikapun ada aktor masyarakat sipil yang masuk tubuh parpol, suara mereka tergerus oleh suara para penentu keputusan dan jaringan pendukung kaum oligarki di dalam tubuh parpol. Abdil Mughis Mudhoffir dan Andi Rahman Alamsyah menjelaskan bahwa para aktivis yang menjadi aktor masyarakat sipil tak berdaya ketika harus berhadapan dengan kaum oligarki dalam tubuh parpol sehingga reformasi politik nihil terlaksana.
Kedua, pers yang juga digembosi oleh kaum oligarki maupun oleh produk hukum yang mengekang. Para oligarki mendirikan media pers sendiri dan mengelolanya untuk kepentingan pribadi. Wisnu Prasetya Utomo menyebutkan bahwa kaum oligarki media dapat leluasa menentukan kebijakan pemberitaan demi menggiring opini untuk berpihak pada politik sektarian parpol atau figur tertentu. Di lain sisi, jikapun ada media massa yang tetap independen dan berada pada jalur demokrasi yang dengan vokal mengkritik penguasa seringkali dituding melakukan penghinaan maupun ujaran kebencian sehingga terjerat pasal karet dalam UU ITE.
Ketiga, mahasiswa dan akademisi yang menjadi representasi perguruan tinggi dalam praktik demokrasi masyarakat sipil juga digembosi ketika mereka dengan lantang menyuarakan aspirasi rakyat. Banyak mahasiswa dan akademisi lain yang tidak satu visi dengan rekan seperjuangannya karena mendengar dengungan dari buzzer ‘pendengung’ yang menggiring opini publik bahwa demonstrasi berupaya menggulingkan kekuasaan pemerintahan, menggagalkan pelantikan, hingga ditunggangi kepentingan kelompok tertentu. Hal tersebut semakin membuka fakta bahwa banyak aktor intelektual yang tidak satu visi, entah karena merasa demonstrasi tidak ada gunanya, direpresi oleh pihak kampus, hingga terafiliasi dengan penguasa dan jaringannya.
Keempat, terseretnya aktor masyarakat sipil ke dalam politik praktis. Hal ini dibahas dalam sebuah buku berjudul Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan (2010) yang diedit oleh Khamami Zada dan A. Fawaid Sjadzili. Dijelaskan bahwa salah satu organisasi keagamaan (NU) menjadi pilar masyarakat sipil hingga runtuhnya Orde Baru, tetapi mulai tergoda politik praktis ketika era reformasi. Misalnya, masuknya Hasyim Muzadi dalam bursa calon wakil presiden mendampingi Megawati dan ketika Ma’ruf Amin juga terseret politik praktis saat ditunjuk untuk mendampingi Jokowi.
Lebih lanjut, masyarakat sendiri yang tidak lagi mengusung semangat masyarakat sipil karena telah terpolarisasi. Politik sektarian yang dinarasikan dalam pilpres seringkali membuat masyarakat terpolarisasi. Akhirnya, gelombang distrust ‘ketidakpercayaan’ antarkelompok masyarakat pun terjadi. Mereka saling bermusuhan karena perbedaan preferensi politik. Kenneth Newton (2001) menyebutkan bahwa kepercayaan (trust) merupakan modal sosial bagi masyarakat sipil untuk mengawal demokrasi guna menghindarkan masyarakat dari kekuasaan yang sewenang-wenang.
Jika kepercayaan telah terkikis, yang terjadi dalam masyarakat justru intoleransi sehingga visi kolektif untuk mengawal demokrasi menjadi sangat sulit dipersatukan. Rakyat perlu membangun kembali kepercayaan dan loyalitas satu sama lain diperlukan demi melawan kekuasaan yang sewenang-wenang; menciptakan arah langkah yang jelas dalam pembekalan kapasitas politik dan ekonomi yang memadai; berjuang menciptakan ruang-ruang konsolidasi intelektual; hingga mengintegrasikan visi kolektif melalui gerakan terbuka menjadi urgensi yang perlu dilaksanakan. Dengan begitu, pilar-pilar yang kuat dari bawah juga akan memperkuat daya tawar moralitas dan intelektualitas kepemimpinan di masa depan.
Yukaristia.
Lulusan S1 Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Malang. Kini, menjadi guru ekonomi
di salah satu sekolah swasta di daerah Pakuwon City, Surabaya.
Daftar Pustaka:
Jensen, C., Michael. William H. Meckling. 1997. “Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure” dalam Journal of Financial Economics. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X
Mudhoffir, Abdul Mughis dan Andi Alamsyah Rahman. 2018. “Buasnya Sistem Politik Indonesia Halangi Upaya Reformasi dari Dalam oleh Mantan Aktivis” The Conversation. https://theconversation.com/buasnya-sistem-politik-indonesia-halangi-upaya-reformasi-dari-dalam-oleh-mantan-aktivis-94523
Newton, Kenneth. “Trust, Social Capital, Civil Society, and Democracy.” International Political Science Review / Revue Internationale de Science Politique 22, no. 2 (2001): 201–14. http://www.jstor.org/stable/1601186.
Orwell, George. 2016. 1984. Bentang Pustaka.
Sjadzili, Khamami, Zada;, A., Fawaid. 2010. Nahdlatul Ulama, Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J.P. (2011). Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto bukan Tolok Ukur yang Tepat untuk Menilai Kemajuan? (M. Arumsari & F. B. Timur, Penerjemah). Tangerang: Marjin Kiri.
Utomo, Wisnu Prasetyo. 2017. “Oligarki Media dan Bagaimana Dia Menentukan Arah Pemberitaan” The Conversation. https://theconversation.com/oligarki-media-dan-bagaimana-dia-menentukan-arah-pemberitaan-86639