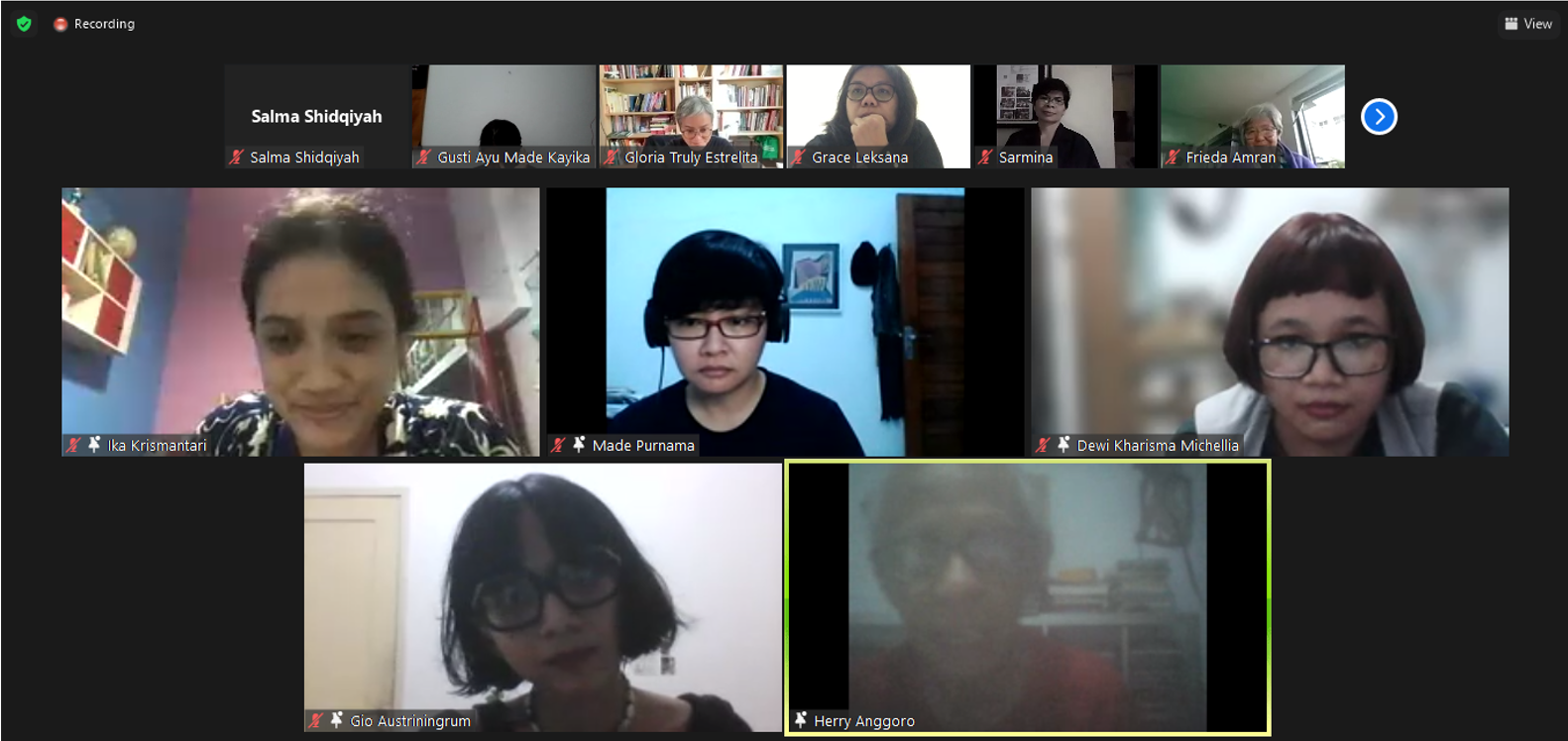
Forum diskusi Warisan Ingatan yang diinisiasi oleh para seniman dan aktivis menggelar diskusi Seri Warisan Ingatan 8. Seri ini bertajuk “Yang Dihilangkan Dari Sejarah Perempuan dan Sastra Modern Indonesia” yang dilakukan secara daring. Diskusi ini mengulas sosok sastrawan perempuan indonesia, yakni Rukiah Kertapati dan Sugiarti Siswadi. Pembahasan diskusi ini dilakukan dengan menghadirkan narasi perspektif perempuan pada era revolusi nasional dan pasca-Kemerdekaan. Acara yang digelar pada Kamis (11-11), dimoderatori oleh Ika Krismantari dari Ingat 65. Dengan menghadirkan Giovanni Austriningrum dan Ni Made Purnamasari dari Ruang Perempuan dan Tulisan (RPDT) sebagai pembicara. Selain itu, terdapat Yerry Wirawan sebagai pengantar diskusi yang merupakan seorang sejarawan.
Yerry mengawali acara dengan menuturkan bahwa hakikat sejarah merupakan platform atau batasan yang pernah terjadi di masa lalu. Dia menjelaskan bahwa dalam periode sejarah Indonesia, pada tahun 1960-an, terdapat penulis-penulis wanita yang mencita-citakan keadilan sosial demokratis melalui karya sastra. Dia menambahkan, diskusi ini bertujuan untuk mengukirkan kembali sejarah perjuangan tersebut.
Menurut ika terdapat beberapa nama penulis wanita, seperti Rukiah Kertapati dan Sugiarti Siswadi yang masih terasa asing di kancah sastra Indonesia. Ia menambahkan, nama mereka tak pernah tercatat. “Alasan nama mereka terlupakan kental dengan afiliasi politik pada Orde Baru,” tutur Ika.
Gio menyebutkan, karya Rukiah merupakan karya semi-autobiografi yang terinspirasi dari kehidupannya sendiri. Rukiah banyak bertemu dengan prajurit Laskar Rakyat Djakarta Raya yang memicu ketertarikannya pada politik sosialis serta aktif dalam komunitas Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) dan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). “Rukiah tidak menelan mentah-mentah ide sosialis, tetapi menelaahnya kembali bahkan karirnya melejit saat berumah tangga,” tambahnya. Menurutnya, semangat menulis Rukiah tak pudar yang ditunjukkan dengan keaktifannya menulis sastra anak. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa sastra anak menjadi tempat ekspresi Rukiah untuk mendorong rasa empati dan kritis pemuda dalam memahami nasionalisme dan antikolonialisme.
Lebih lanjut, Gio menjelaskan bahwa di tengah kemajuan karirnya, Rukiah menjadi salah satu sasaran insiden 65. Akibatnya, ia selalu diawasi dan mesin ketiknya dirampas. “Setelah pembungkaman tersebut, Rukiah mengalami trauma menulis sehingga tidak mampu menciptakan tulisan kembali, bahkan tulisannya sempat dilarang,” terang Gio. Ia menambahkan, karya Rukiah ditemukan kembali pada tahun 1977 dan dimasukkan dalam Antologi Tulisan Perempuan Indonesia. Setelah Rukiah wafat, karyanya banyak diteliti dan diterbitkan kembali.
Dengan berterus terang, Gio mempunyai kesan pribadi terhadap kisah Rukiah. Menurutnya, kisah Rukiah mengilustrasikan tanggung jawab wanita dalam berumah tangga sembari berkarir. Narasi heroik karya Rukiah dari wacana negara sampai kehidupan sehari-hari digambarkan dengan jujur, kritis, dan melampaui batas-batas di masa bergejolak. Ia menambahkan, Rukiah mampu memberikan warna selain hitam putih pada karakter dalam ceritanya sehingga mengubah perspektif mengenai rakyat biasa yang dianggap lemah pada masa itu.
Made menerangkan bahwa kronik kehidupan Sugiarti Siswadi tidak sejelas Rukiah Kertapati. Ia juga menambahkan bahwa mereka sebenarnya rekan yang sangat dekat, tetapi ternyata memiliki nasib yang berbeda. ”Sosok Sugiarti bisa dibilang samar, tak seperti kehidupan Rukiah yang masih bisa dilacak,” ujar Made.
Mengenai karya karya-karya Sugiarti, Made menyatakan bahwa RPDT telah melacak karya Sugiarti di Pusat Dokumentasi Sastra Hans Bague Jassin. Ia menjelaskan pada tempat itu ditemukan satu buku arsip karya Sugiarti yang berjudul Sorga di Bumi. Buku ini dicetak oleh Lekra pada tahun 1960 dan dilarang pada masa Orde Baru. Ia juga menambahkan bahwa karya-karya Sugiarti tersebar di majalah Api Kartini yang digagas oleh Sugiarti.
Berdasarkan hasil penelusurannya, Made menjelaskan, saat ini akses untuk membaca karya tersebut sangat terbatas. Karya tersebut bahkan tidak diterbitkan ke toko buku dan hanya beberapa perpustakaan yang menyimpan arsip karya tersebut, contohnya perpustakaan UI. Ia juga menyatakan harapannya terhadap sastra perempuan di Indonesia. “Proyek RPDT berharap karya-karya sastra semacam ini yang dahulunya dilarang dan tidak dicetak ulang untuk segera mendapat digitalisasi,” pungkasnya.
Penulis: Herlina Rifa Paramartha, Salma Shidqiyah, Ananda Ridho Sulistya (Magang)
Penyunting: Fahmi Aryo Majid
Fotografer: Zidane Damar (Magang)