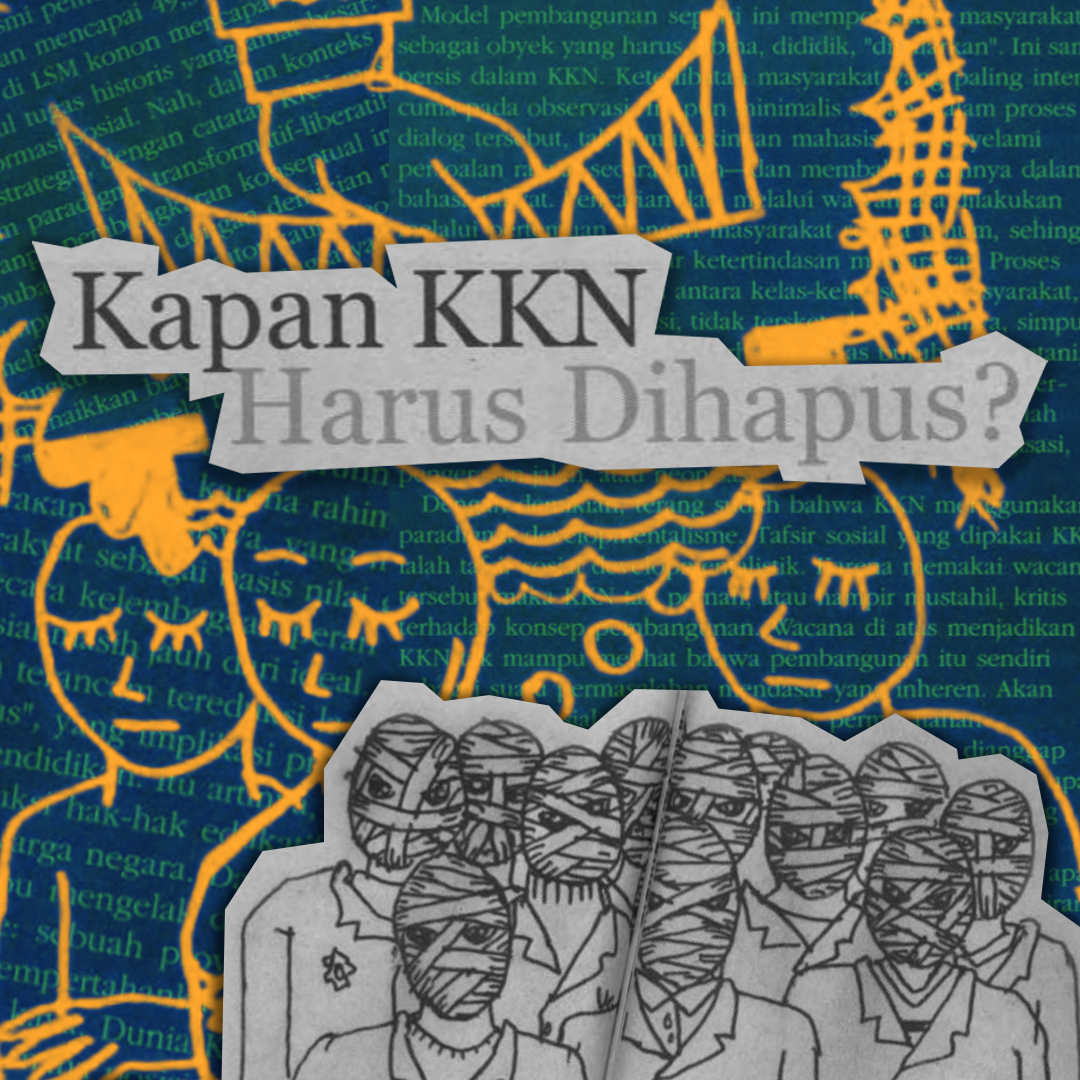
©Sutanto/BAL
Sekurang-kurangnya sejak 1979, Kuliah Kerja Nyata (KKN) telah menjadi program wajib yang mesti diikuti setiap mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia, selain hadir sebagai penuntasan atas Tridharma Perguruan Tinggi, nyatanya juga berjalan sebagai cara UGM untuk terus melap-lap citra “kampus kerakyatan”. Dari sini, sebuah masalah timbul: “kerakyatan” dimaknai sebagai usaha untuk menuntun masyarakat menuju “kemajuan”. “Kemajuan”, tentu, merupakan istilah yang mencurigakan. Ia sarat dengan agenda pembangunan dan kerap menjadi panji untuk proyek modernisasi yang gegabah.
Kegegabahan ini nyatanya terus dilanjutkan. Dalam tulisannya di rubrik “Opini” dalam Majalah BALAIRUNG Edisi Khusus/TH.XV/1999, Muhammad Mustafied menanggapi permasalahan ini dengan memperlihatkan kekeliruan mendasar dari paradigma pengabdian yang berbasis pembangunan: ia tidak menempatkan permasalahan dan kepentingan masyarakat sebagai hal yang utama. Masyarakat diposisikan sebagai objek tertinggal yang tidak memahami permasalahannya sendiri sehingga harus “dinalarkan” agar tegak lurus dengan arah pembangunan dan modernisasi. Berikut tulisan selengkapnya.
Apa yang terlintas dalam benak kita begitu mendengar nama Universitas Gadjah Mada (UGM)? Ternyata, banyak hal. Satu di antaranya adalah mitos “kampus kerakyatan”. UGM sering diidentikkan dengan kampus kerakyatan. Ungkapan ini tak seluruhnya salah, tetapi tak sepenuhnya benar. Benar, karena rahim sosial UGM telah melahirkan gerakan mahasiswa yang menjadikan ketertindasan rakyat sebagai basis nilai gerakan dan refleksi. Salah, sebab secara kelembagaan, peran UGM dalam transformasi sosial masih jauh dari ideal.
Ini pun masih terancam tereduksi lagi dengan proyek “otonomi kampus” yang implikasi praksisnya langsung terasa: naiknya biaya pendidikan. Itu artinya, institusi ini secara sistematis mereduksi hak-hak edukatif rakyat-miskin yang inheren sebagai warga negara. Dalam skala makro, UGM ternyata tak mampu mengelak dari hegemoni developmentalisme: sebuah proyek kapitalisme yang berkepentingan untuk mempertahankan status ketergantungan antara kaum miskin-kaum kaya, Dunia Ketiga-Dunia Pertama. Bila demikian halnya, di mana posisi tugas dan peran UGM sebagai penggerak transformasi sosial sehingga layak mengklaim diri sebagai kampus kerakyatan?
Tulisan ini mencoba merefleksikan hal tersebut. Sebagai basis material, tulisan ini memfokuskan pada objek Kuliah Kerja Nyata (KKN) UGM yang, secara akademik, dipahami sebagai salah satu manifestasi “pengabdian kepada masyarakat”. Konstruksi wacananya berbasiskan pengalaman penulis mengikuti KKN periode semester pendek 1998/1999 dan pembacaan terhadap konsep KKN yang dikaitkan dengan dua hal: tugas transformasi sosial dan rencana “otonomi kampus”—atau komersialisasi pendidikan. Sebagai jendela fenomenologis, KKN akan dilihat dari dua sisi, yakni sisi konseptual dan sisi praktikal.
Konseptualisasi KKN
KKN secara normatif diposisikan sebagai salah satu pengejawantahan konsep pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan satu dari tiga serangkai konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi (PT). Dua yang lainnya ialah kegiatan pendidikan dan penelitian. Falsafah dasar pengabdian masyarakat, seperti ditulis A. Samik Wahab dalam Buku Panduan KKN (1998), adalah “pemindahan ilmu, sikap, dan keterampilan dari universitas ke masyarakat”. Sedangkan tujuan dasar KKN, menurut uraian M. Mansykur Rahmat (Ibid.), ada tiga: (1) agar PT menghasilkan sarjana sebagai “penerus pembangunan” yang menghayati masalah yang sangat kompleks dihadapi oleh masyarakat dalam pembangunan dan yang belajar menanggulangi masalah-masalah tersebut secara pragmatis dan interdisipliner; (2) untuk lebih mendekatkan Lembaga PT pada masyarakat dan menyesuaikan PT kepada “tuntutan pembangunan”; dan (3) mengembangkan kerja sama antardisiplin ilmu. Sedangkan sasaran KKN diarahkan pada tiga sasaran: mahasiswa sebagai calon penerus pembangunan, universitas sebagai tempat mahasiswa belajar, serta masyarakat yang dibantu oleh para mahasiswa.
Tulisan ini, selanjutnya, hendak mengevaluasi KKN, dengan pemfokusan pada “sasaran untuk mahasiswa dan masyarakat”. Secara teoritis, KKN diarahkan pada mahasiswa dengan tujuan, antara lain, untuk (a) memperdalam pengertian dan penghayatan mahasiswa tentang cara berpikir dan bekerja interdisipliner, kegunaan pendidikannya bagi pembangunan, pengetahuan akan kesulitan masyarakat desa dalam pembangunan pengembangan daerah pedesaan; (b) mendewasakan alam pikiran mahasiswa dalam setiap penelahaan dan pemecahan masalah yang ada di masyarakat secara pragmatis-ilmiah; (c) memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan program-program pengembangan dan pembangunan desa; (d) membina mahasiswa agar menjadi seorang inovator, motivator, dan problem solver, serta (e) memberikan pengalaman dan keterampilan kepada mahasiswa sebagai “kader pembangunan”.
Sedangkan bagi masyarakat, sasaran itu dirumuskan sebagai berikut: (a) memperoleh bantuan dan pikiran untuk merencanakan serta melaksanakan “proyek pembangunan”; (b) cara berpikir, bersikap, dan bertindak akan lebih ditingkatkan sehingga sesuai dengan “program pembangunan”; (c) memperoleh pembaharuan-pembaharuan; dan (d) terbentuknya “kader-kader pembangunan” dalam masyarakat sehingga terjamin terbentuknya penerus-penerus pembangunan.
Praktik KKN
Pelaksanaan KKN memerlukan waktu minimal dua bulan. Pada minggu pertama, tugas mahasiswa adalah melakukan observasi lapangan sebagai dasar dalam menentukan program. Dalam observasi ini mahasiswa diharuskan mengidentifikasi seluruh permasalahan yang ada, untuk kemudian diseleksi berdasarkan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat) guna perumusan program individual.
Pada tahap selanjutnya, yakni minggu ke-2 hingga ke-7, mahasiswa melaksanakan program kerjanya. Pelaksanaan program kerja ini dimungkinkan untuk diubah atau ditambah tergantung perkembangan situasi dan kondisi yang barangkali belum tercakup pada perumusan masalah dan pemilihan program. Program kerja yang digarap meliputi empat wilayah besar: prasarana fisik, sosial-budaya, kesehatan masyarakat, dan peningkatan produksi. Pluralitas wilayah kerja inilah yang memungkinkan setiap mahasiswa untuk merancang programnya secara interdisipliner. Tahap terakhir, yakni minggu ke-8, merupakan masa penghentian seluruh kegiatan mahasiswa dan diisi dengan penulisan laporan kerja hingga penarikan unit KKN.
Demikianlah selintas konsep dan praktik KKN-UGM. Sebagaimana diketahui, beberapa universitas, seperti UI, ITB, IPB, dan terakhir UNS, menghentikan program ini dengan alasan masing-masing. UGM sebagai konseptor dan pencetus gagasan ini hingga kini masih tetap melaksanakannya.
KKN dan Ideologi Developmentalisme
Begitu membaca konsep KKN di atas, siapapun akan dengan segera menghirup bau menyengat atmosfer developmentalisme. Bertebaran kata-kata pembangunan yang bertendensi ideologis-developmentalistik, tanpa mengindikasikan suatu sikap kritis. Perhatikanlah kalimat-kalimat berikut ini: “…agar Lembaga PT menghasilkan sarjana sebagai ‘penerus pembangunan’, yang lebih menghayati masalah yang sangat kompleks dihadapi oleh masyarakat dalam pembangunan dan lebih menyesuaikan PT kepada ‘tuntutan pembangunan’”; “mengetahui kesulitan masyarakat desa dalam pembangunan dan konteks keseluruhan masalah pembangunan pengembangan pedesaan”; “memberikan pengalaman dan keterampilan kepada mahasiswa sebagai ‘kader pembangunan’”; “agar cara berpikir, bersikap, dan bertindak akan lebih ditingkatkan dan sesuai dengan ‘program pembangunan’”; “memperoleh pembaharuan-pembaharuan”; “terbentuknya ‘kader-kader pembangunan’…”; dst.
Mulai dari falsafah, asas, tujuan, sasaran, hingga praksis KKN dikonseptualisasikan berdasarkan paradigma developmentalisme. Seluruh konsep di atas dibangun atas dasar asumsi-asumsi wacana developmentalistik yang melihat masyarakat dengan kacamata teori pembangunan (modernisasi). Dalam teori tersebut diandaikan setiap masyarakat akan mengikuti proses sebagaimana dialami negara-negara modern. Salah satu rujukan teoritis konsep itu ialah Walt W. Rostow dengan teori lima tahap perkembangan masyarakat. Menurutnya, proses pembangunan berjalan sesuai tahap-tahap pertumbuhan sebagaimana negara modern mengalaminya. Mansour Fakih (1996: 70) menulis bahwa pembangunan dipahami sebagai proses tahap demi tahap menuju “modernitas”. Modernitas ini tercermin dalam bentuk kemajuan teknologi dan ekonomi seperti yang dilalui oleh bangsa-bangsa industri maju.
Target atau sasaran yang hendak dicapai KKN, seperti meningkatkan cara berpikir, bersikap, bertindak agar sesuai dengan program pembangunan atau agar terjadi pembaharuan-pembaharuan, sebangun dengan paradigma modernisasi. Encyclopaedia of The Social Science (1996), seperti dikutip Mansour Fakih (1996: 72), merumuskan “modernisasi yang sebangun dengan pembangunan” meliputi:
…sekularisasi; komersialisasi; industrialisasi; peningkatan standar hidup materi; penyebaran melek huruf; pendidikan, media massa, persatuan nasional; dan perluasan keterlibatan rakyat dalam partisipasi.
Model pembangunan seperti ini memosisikan masyarakat sebagai objek yang harus dibina, dididik, “dinalarkan”. Ini sama persis dalam KKN. Keterlibatan masyarakat yang paling intens cuma pada observasi. Ini pun minimalis, sebab, dalam prosesnya mahasiswa tak dimungkinkan untuk menyelami persoalan rakyat secara intim—dan membahasakannya dalam bahasa rakyat. Pencarian data melalui wawancara dilakukan melalui pertemuan dengan masyarakat secara umum sehingga tak teridentifikasi struktur ketertindasan masyarakat. Proses hegemoni dan dominasi antara kelas-kelas sosial masyarakat, penguasa, dan kaum borjuasi menjadi tidak tersketsakan. Misalnya, simpul hegemoni dan domestikasi terhadap kelas buruh atau petani, yang hampir pasti ada dalam setiap tempat KKN, tidak tercakup. Yang muncul ke permukaan justru masalah-masalah pembangunan fisik kampung atau dusun, seperti pemasangan plang, pengerasan jalan, atau pemasangan lampu neon.
Dengan demikian, terang sudah bahwa KKN menggunakan paradigma developmentalisme. Tafsir sosial yang dipakai KKN ialah tafsir sosial developmentalistik. Karena memakai wacana tersebut maka KKN tak pernah, atau hampir mustahil, kritis terhadap konsep pembangunan. Wacana di atas menjadikan KKN tak mampu melihat bahwa pembangunan itu sendiri sebagai suatu permasalahan mendasar yang inheren. Akan tetapi, tafsir sosial KKN justru melihat permasalahan pembangunan lebih disebabkan oleh masyarakat yang dianggap kurang terdidik. Maka, dapat ditebak bahwa KKN sibuk dengan upaya mengubah nalar masyarakat yang, konon, “tak bernalar”. Yang nalar hanyalah yang rasional-empiristik (terukur, teraba, terindra) sebab di sanalah terkandung kebenaran. Karena yang didekati oleh KKN pada dasarnya merupakan pinggiran-pinggiran atau ekses dari pembangunan, maka KKN tak pernah berhasil menembus hakikat persoalan sosial yang digumuli masyarakat.
Realitas tersebut menghadirkan suatu persoalan yang menggelisahkan sebab KKN tak mempersoalkan mengapa terjadi realitas seperti ini: ada sebagian masyarakat yang sudah memasuki tahapan industrialis berikut segenap ekses ekonomi dan politiknya sedangkan terdapat—sebagian besar—masyarakat yang masih hidup dalam lilitan kemiskinan dengan segala ketertindasan yang dialami. Wacana developmentalis di atas, selain menghegemonikan diskursus tugas pendidikan, juga berimplikasi serius pada dataran praksis. Dalam merumuskan programnya, KKN tidaklah berangkat dari realitas ketertindasan dan keterpinggiran masyarakat akar rumput. Penyusunan program kerja juga tak didasarkan pada hakikat terdalam persoalan sosial. Pembangunan dianggap sebagai sesuatu yang benar dan tak diragukan. Dus, musuh utama pembangunan adalah nalar masyarakat yang dianggap masih primitif dan irasional sehingga perlu diubah.
Akan tetapi, tanpa mengandaikan terpahaminya struktur relasi kuasa, KKN langsung disusun berdasarkan observasi lapangan lewat wawancara dengan anggota masyarakat dan perangkat pemerintahan. Observasi diharapkan pula mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan pokok masyarakat, kemudian dengan “ambisius” hendak diselesaikan persoalan tersebut. Oleh karena tidak memandang pembangunan sebagai bagian dari persoalan dan tak memakai perspektif kritis, maka program-program kerjanya berada di luar lintasan persoalan sosial yang tengah digumuli oleh masyarakat. Perhatikanlah daftar program kerja sebagai berikut: pemasangan plang, pengecatan gapura/pos ronda, pembangunan jalan, penyuluhan-penyuluhan, penerangan menggunakan lampu neon, pasar murah, pembinaan PKK, dll. Pendek kata, keempat wilayah bidang kerja boleh dikatakan hampir semuanya program-program “karikatural” dan gagal menggerakkan transformasi sosial masyarakat.
Sebagai catatan, sebagian program sebenarnya lumayan konstruktif, seperti pembangunan jalan, penyuluhan ekonomi kecil, pembinaan kepemudaan. Namun, sayang, program itu berjalan tanpa disertai proses penyadaran tentang hak-hak sipil dan politik warga negara, suntikan ide-ide dan gagasan progresif yang dapat terus berdialektika di masyarakat sekalipun telah ditarik. Jadinya, pembangunan jalan atau peningkatan ekonomi, misalnya, seolah-olah hanya bersentuhan dengan kewajiban masyarakat yang tak berkaitan apa-apa dengan struktur kuasa dan kapitalisme. Tak terjadi transformasi kesadaran bahwa akses ekonomi, politik, atau informasi merupakan hak inheren sebagai warga negara. Hubungan penguasa dan rakyat tetap dipahami dengan logika tuan-hamba dan bukan sebaliknya. Atau pembinaan kepemudaan—PKK dan karang taruna—hanya pada persoalan administratif. Tak terjadi transformasi kesadaran historis pada generasi muda bahwa merekalah minoritas kreatif yang mampu menggerakkan perubahan. Pengalaman penulis menunjukkan hal itu. Ketika hendak dilaksanakan program civic education bagi generasi muda sempat dipertanyakan oleh DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) dan juga aparat pemerintah.
Implikasi sosial dari semua itu adalah KKN—disadari atau tidak, langsung atau tidak langsung—justru terjebak dalam lingkaran hegemoni developmentalisme dan ikut berperan dalam pelestarian struktur ketertindasan masyarakat. Escobar (1990: 7, dalam Mansour Fakih, 1996: 74) menggambarkan proses hegemoni penyebar-serapan diskursus developmentalisme ini melalui:
…penciptaan jaringan kerja kelembagaan luas (dari organisasi internasional dan universitas hingga pelaku pembangunan tingkat lokal)… Sekali dikonsolidasikan, sistem ini menentukan apa yang dapat dikatakan, dipikirkan, dibayangkan; singkatnya, sistem itu mendefinisikan bidang perseptual ruang pembangunan.
Mengapa? Sebab KKN tak memberikan penyadaran atau perspektif pada rakyat tentang terjadinya realitas kontras antara masyarakat borjuis dan proletar. KKN justru meninabobokkan rakyat dengan mencekoki bahwa permasalahan-permasalahan ini dikarenakan nalar dan sikap mental yang kurang sesuai dengan pembangunan sehingga mereka tertinggal. Maka, terapi yang diambil ialah mengubah nalar dan sikap mental rakyat agar kondusif bagi proyek modernisasi.
Catatan Akhir
Survei singkat di atas menyimpulkan bahwa konsep dan praktik KKN layak ditinjau ulang apabila diletakkan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat. Bila tidak, maka pengabdian pada masyarakat, sebuah kesadaran nan tulus, justru menjadi instrumen kapitalisme dalam menghegemoni dan menumpulkan sikap kritis masyarakat.
Dengan melihat latar sosial masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih tertindas (angka resmi pemerintah pada tahun 1999, rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan mencapai 49,3 juta, sedangkan angka yang beredar di LSM konon mencapai 100 juta-an). Maka UGM memikul tugas historis yang amat besar: menggerakkan transformasi sosial. Nah, dalam konteks inilah KKN memiliki nilai strategis, dengan catatan KKN mesti dirumuskan ulang dalam paradigma transformatif-liberatif-emansipatoris.
Tanpa pembongkaran konseptual ini akan lebih baik KKN dibubarkan—dan dengan demikian menegaskan keberadaan kampus sebagai operator kaum neoliberal. Atau, dengan melihat juta-an generasi bangsa yang dipaksa meninggalkan bangku sekolah karena belitan ekonomi, masih tegakah UGM menaikkan biaya pendidikan atas nama efisiensi dan efektifitas?
Ditulis dengan penyuntingan oleh Giovanni Ramadhani.